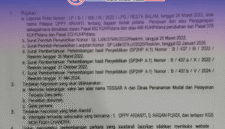Oleh : Refky Rinaldy, S.Sos (Tukang Tulis)
Sebuah Renungan untuk Bangsa
Pada Rabu siang, sekitar pukul 12:30 WITA, langit Indonesia kembali berselimut duka. Di sebuah sudut terpencil negeri ini tepatnya di Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang anak berusia 10 tahun berinisial YBR memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang tak seharusnya pernah terlintas dalam benak seorang bocah seusianya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
YBR, siswa kelas IV Sekolah Dasar itu, meninggalkan selembar surat yang ditulis dengan tinta kesedihan mendalam untuk sang ibu :
“Kertas Tii Mama Reti (Surat Untuk Mama Reti)
Mama Galo Zee (Mama Pelit Sekali)
Mama Molo Ja’o Galo Mata Mae Rita Ee Mama (Mama Baik Sudah. Kalau saya meninggal mama jangan menangis)
Mama jao Galo mata mae woe Rita ee gae ngao ee (Mama saya meninggal, jangan menangis juga jangan cari saya ee)
Molo mama (selamat tinggal mama)”
Kata-kata itu bukan sekadar pesan perpisahan. Ia adalah tangisan hati seorang anak yang merasa menjadi beban, yang menganggap ketidakmampuan membeli buku adalah aib yang harus ditebus dengan nyawa. Betapa tragisnya, ketika pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan harapan justru menjadi jurang pemisah antara hidup dan mati seorang anak bangsa.
Api Kemiskinan yang Tak Kunjung Padam
Tragedi YBR bukan sekadar peristiwa individual. Ia adalah alarm keras yang memekakkan telinga, simbol kegagalan kolektif kita sebagai bangsa. Di balik kematian YBR, terbentang narasi kelam tentang kemiskinan struktural yang belum terhempas, tentang kesenjangan pendidikan yang masih menganga lebar, dan tentang ribuan anak Indonesia lainnya yang mungkin sedang berjuang dalam kesunyian serupa.
Bagaimana mungkin, di negara yang mengklaim telah merdeka selama hampir delapan dekade, seorang anak usia 10 tahun harus memilih mati karena tidak mampu membeli buku? Bagaimana mungkin sistem pendidikan kita membiarkan seorang siswa merasa begitu terpojok hingga bunuh diri menjadi satu-satunya jalan keluar yang ia lihat?
Pertanyaan-pertanyaan ini menohok. Dan jawaban atas pertanyaan ini tidak boleh lagi ditunda.
Pesan untuk Lampung, Cermin untuk Indonesia
Saya, Refky Rinaldy, berbicara bukan dari menara gading kekuasaan. Saya bukan pejabat, bukan keturunan elit. Saya hanyalah warga biasa dari Tanah Lampung yang merasakan pedih yang sama dengan jutaan rakyat Indonesia lainnya ketika mendengar berita ini.
Kepada seluruh unsur pemerintahan, dari tingkat Kabupaten, Kota, hingga Provinsi Lampung, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Lihatlah YBR. Dengarkan tangisannya yang tertuang dalam surat perpisahan itu. Jadikan tragedi ini sebagai cermin untuk memeriksa kembali, apakah di Lampung, di kampung-kampung terpencil kita, ada YBR-YBR lain yang sedang berjuang dalam sunyi?
Jangan anggap ini sebagai kejadian jauh yang tak ada kaitannya dengan kita. Kemiskinan tidak mengenal batas administratif. Penderitaan anak-anak tidak memilih geografis. Apa yang terjadi di NTT hari ini bisa saja terjadi di Lampung besok, jika kita tidak segera bergerak dengan hati nurani yang terjaga.
YBR: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Izinkan saya menyebut YBR sebagai pahlawan. Bukan karena kematiannya, tetapi karena melalui tragedi yang menimpanya, ia telah memaksa kita semua untuk membuka mata. YBR adalah pengingat bahwa di balik statistik kemiskinan dan angka putus sekolah, ada wajah-wajah anak dengan mimpi yang sama besarnya dengan anak-anak lain, tetapi dengan kesempatan yang jauh lebih sempit.
Kematian YBR haruslah menjadi titik balik. Ia harus menjadi katalisator bagi perubahan nyata dalam kebijakan pendidikan dan kesejahteraan anak. Tidak boleh ada lagi anak yang merasa bahwa ketidakmampuan membeli buku adalah alasan untuk mengakhiri hidup. Tidak boleh ada lagi anak yang merasa menjadi beban hanya karena keluarganya miskin.
Seruan untuk Bertindak
Kepada para Kepala Daerah, Legislator, dan seluruh Aparatur Pemerintahan di Lampung dan Indonesia:
Periksalah kembali sistem bantuan pendidikan di daerah Anda. Pastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang terhambat aksesnya terhadap pendidikan karena alasan ekonomi. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan berbagai skema kesejahteraan lainnya harus benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan, bukan hanya tertulis di laporan, tetapi nyata di lapangan.
Bentuklah sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko mengalami tekanan psikologis akibat kondisi ekonomi. Libatkan guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam jejaring pengawasan yang penuh kasih sayang, bukan pengawasan yang menghakimi.
Bekerjanlah dengan hati, bukan hanya dengan angka. Kesejahteraan rakyat bukan sekadar capaian indeks atau ranking. Ia adalah tentang memastikan setiap anak bisa tidur nyenyak tanpa beban, bangun pagi dengan harapan, dan pergi ke sekolah dengan senyuman.
Doa untuk YBR, Janji untuk yang Hidup
YBR, di mana pun engkau berada saat ini, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih mengampuni segala dosa dan khilafmu. Semoga engkau menemukan kedamaian yang tak pernah engkau temukan di dunia ini. Jasadmu mungkin telah tiada, tetapi pesan yang engkau tinggalkan akan terus bergema, menggugah nurani bangsa ini.
Untuk kita yang masih hidup, tragedi YBR adalah amanah. Amanah untuk memastikan tidak ada lagi anak yang mengalami nasib serupa. Amanah untuk membangun Indonesia yang lebih adil, lebih peduli, lebih manusiawi.
Mari kita jadikan duka ini sebagai energi perubahan. Mari kita wujudkan Indonesia di mana setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi, belajar, dan tumbuh menjadi manusia seutuhnya.
Tulisan ini lahir bukan dari keinginan untuk menggurui, melainkan dari kepedulian seorang warga negara yang tidak ingin melihat tragedi serupa terulang. Jika ada kata-kata yang keliru atau menyinggung, saya mohon maaf. Yang saya tulis adalah apa yang saya rasakan—sebagai manusia, sebagai anak bangsa, sebagai sesama yang peduli.